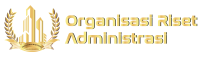Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) adalah organisasi kepemudaan yang lahir dari semangat ajaran marhaenisme—ideologi yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno—dan dikenal sebagai bagian dari barisan pendukung nasionalisme dan rakyat kecil. Selama masa Orde Lama, GPM menjadi salah satu kekuatan politik yang mendukung penuh pemerintahan Soekarno. Namun, pada masa Orde Baru, GPM menghadapi tekanan luar biasa dan perlakuan represif dari rezim militeristik yang berkuasa.
GPM tidak hanya menjadi wadah kaderisasi ideologi Marhaen, tetapi juga menjadi bagian dari perlawanan intelektual dan politik terhadap otoritarianisme. Peran serta GPM dalam mempertahankan warisan politik Bung Karno menjadikannya target pembungkaman oleh rezim Soeharto, yang menganggap gerakan semacam ini sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan.
Artikel ini akan membahas asal-usul GPM, perannya di masa Orde Lama, tekanan yang dihadapinya di era Orde Baru, serta warisan ideologinya dalam gerakan pemuda Indonesia.
Latar Belakang Gerakan Pemuda Marhaenis

1. Lahirnya GPM dari Akar Nasionalisme
Gerakan Pemuda Marhaenis muncul sebagai bagian dari gerakan nasionalis progresif yang berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an. Didorong oleh semangat ajaran Soekarno, GPM mengusung ideologi marhaenisme yang bertujuan membela rakyat kecil (kaum marhaen), memberantas imperialisme, dan memperjuangkan keadilan sosial.
GPM menjadikan Soekarno sebagai figur sentral dan menolak segala bentuk dominasi asing maupun kapitalisme yang merugikan rakyat. Mereka aktif dalam pendidikan politik, demonstrasi, serta kegiatan sosial, terutama di kalangan mahasiswa dan pemuda.
2. Kedekatan dengan PNI dan Soekarno
GPM dikenal sebagai sayap kepemudaan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), partai pengetahuan yang juga mendukung Soekarno. Kedekatan ini membuat GPM berperan aktif dalam menyuarakan dukungan terhadap program-program revolusi Soekarno, seperti Demokrasi Terpimpin, konfrontasi melawan Malaysia, dan Trisakti.
Organisasi ini juga menolak kekuatan Islam politik ekstrem dan kapitalisme liberal, dua kekuatan yang kerap dianggap bertentangan dengan marhaenisme.
GPM di Masa Orde Baru: Dari Pendukung Pemerintah Menjadi Musuh Negara
1. Goncangan Pasca-G30S 1965
Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), terjadi perubahan besar dalam peta politik Indonesia. Soekarno secara bertahap kehilangan kekuasaan, dan Jenderal Soeharto mengambil alih melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Pemerintah Orde Baru memulai pembersihan terhadap organisasi-organisasi yang dianggap berhaluan kiri atau pro-Soekarno, termasuk GPM.
GPM dituduh dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena pernah berada dalam satu poros politik Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) yang digagas Soekarno. Akibatnya, kader-kader GPM menjadi korban pembubaran, penangkapan, bahkan penghilangan.
2. Represi Terhadap Kader GPM
Orde Baru menjalankan represi sistematis terhadap GPM. Aktivitas organisasi dibatasi, kantor-kantor ditutup, dan publikasi dibredel. Banyak kader GPM:
-
Diusir dari kampus atau instansi pemerintah
-
Ditangkap tanpa proses hukum
-
Dipaksa menandatangani surat pernyataan berhenti berorganisasi
Sebagian kader memilih untuk melanjutkan perjuangan secara bawah tanah atau menyamar dalam gerakan mahasiswa, khususnya di lingkungan kampus.
3. Perlawanan Intelektual dan Simbolik
Meskipun ditekan, semangat marhaenisme tidak padam. GPM tetap hidup dalam diskusi-diskusi kecil, penerbitan pamflet, dan pengaderan ideologis secara sembunyi-sembunyi. Mereka terlibat dalam gerakan mahasiswa kritis, yang pada akhir 1980-an mulai menentang kebijakan Orde Baru, terutama dalam isu-isu hak asasi manusia dan kebebasan akademik.
Beberapa alumni GPM bahkan menjadi penggerak awal jaringan pro-demokrasi, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan besar dalam gerakan reformasi 1998.
Ajaran Marhaenisme sebagai Pilar Perlawanan

1. Marhaenisme: Ideologi Rakyat Tertindas
Marhaenisme bukan sekadar ideologi, tapi cara berpikir dan bergerak dalam memperjuangkan hak rakyat kecil. Soekarno mendefinisikan marhaen sebagai petani kecil, buruh, dan rakyat yang bekerja namun tertindas oleh sistem kapitalisme dan kolonialisme.
GPM mengusung prinsip bahwa pemuda harus menjadi motor perubahan sosial, berdiri di samping rakyat, dan tidak menjadi kaki tangan kekuasaan. Nilai-nilai ini mereka tanamkan melalui pendidikan politik, organisasi kolektif, dan gerakan akar rumput.
2. Kritik Terhadap Kapitalisme dan Militerisme
Selama Orde Baru yang bercorak kapitalistik dan militeristik, GPM konsisten mengkritik dominasi modal asing, ketimpangan ekonomi, dan militerisasi kehidupan sipil. Walau dalam kondisi ditekan, mereka tetap mengembangkan wacana alternatif dalam ruang-ruang tertutup, seperti kampus, asrama mahasiswa, dan kelompok diskusi.
Mau travel ke mana bulan ini? Cek https://odishanewsinsight.com untuk melihat itinerary juga destinasi wisata terlengkap 2025!
Dampak dan Warisan GPM di Era Reformasi
1. Kelahiran Kembali Gerakan Marhaenisme
Setelah jatuhnya Soeharto pada 1998, banyak organisasi yang mengklaim mewarisi semangat GPM dan marhaenisme. Beberapa kelompok membangkitkan kembali organisasi pemuda marhaenis, baik dalam bentuk partai, lembaga swadaya masyarakat, maupun forum diskusi.
Nama GPM kembali disebut dalam berbagai peringatan sejarah gerakan rakyat dan kegiatan politik pro-rakyat.
2. Kader GPM dalam Politik dan Aktivisme
Banyak mantan kader GPM atau simpatisan marhaenis kemudian terlibat dalam partai politik reformis, organisasi buruh, dan gerakan tani. Sebagian juga aktif dalam pemerintahan lokal atau lembaga legislatif, membawa semangat keadilan sosial yang mereka perjuangkan sejak muda.
3. Inspirasi Bagi Generasi Muda
Di tengah krisis identitas dan apatisme politik generasi baru, warisan GPM menawarkan semangat ideologis yang kuat, berakar pada nasionalisme dan pembelaan terhadap rakyat kecil. Marhaenisme tetap menjadi inspirasi bagi pemuda yang menginginkan perubahan sosial secara mendalam, bukan hanya permukaan.
Kesimpulan
Gerakan Pemuda Marhaenis adalah contoh perlawanan politik yang lahir dari idealisme dan keyakinan terhadap keadilan sosial. Dalam masa Orde Baru yang penuh tekanan, GPM tetap berpegang pada ajaran Bung Karno dan menolak tunduk pada kekuasaan represif.
Meski dibungkam, GPM tidak pernah benar-benar mati. Semangatnya terus hidup dalam gerakan pemuda, aktivisme politik, dan perjuangan sosial di era reformasi. GPM mengajarkan bahwa perlawanan tidak harus selalu lewat kekuatan massa, tapi juga lewat kesetiaan terhadap nilai-nilai perjuangan.
Baca juga artikel berikut: Peristiwa Cumbok Aceh: Konflik Internal di Tanah Rencong