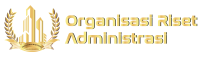Jakarta, adminca.sch.id – Bayangkan sebuah orkestra tanpa dirigen. Masing-masing pemain memainkan nada indah, tetapi jika tak dikendalikan satu suara utama, yang terdengar hanyalah kekacauan. Begitulah koordinasi administrasi publik bekerja dalam tubuh pemerintahan.
Di balik setiap kebijakan pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga tata ruang kota, ada jejaring koordinasi yang berjalan tanpa henti. Koordinasi ini bukan hanya soal rapat antardinas atau surat-menyurat formal, tapi tentang bagaimana berbagai lembaga, kementerian, bahkan pemerintah daerah, saling bersinergi agar satu tujuan besar bisa tercapai: pelayanan publik yang efisien.
Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Di dunia nyata, koordinasi administrasi publik sering kali tersandung pada ego sektoral, birokrasi kaku, atau bahkan teknologi yang belum terintegrasi. Misalnya saja ketika program kesehatan nasional tak bisa dijalankan optimal karena data dari Dinas Kependudukan tidak sinkron dengan BPJS. Atau saat kebijakan transportasi mangkrak hanya karena pemerintah kota dan provinsi tak satu suara.
Dan semua ini, terjadi bukan karena niat buruk. Tapi karena sistem koordinasi yang belum cukup lincah dan adaptif.
Memahami Akar dari Koordinasi yang Buruk

Dari hasil wawancara dengan seorang mantan staf ahli di sebuah kementerian, sebut saja Pak Anton, ada satu pernyataannya yang terngiang hingga kini: “Koordinasi itu seni. Tapi sayangnya, banyak birokrat kita masih memainkannya seperti hitungan matematika.”
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Dalam praktiknya, koordinasi bukan hanya soal struktur, melainkan soal budaya kerja dan komunikasi.
Beberapa akar masalah koordinasi administrasi publik di Indonesia antara lain:
-
Silo Mentality
Setiap lembaga merasa punya “wilayah kekuasaan” sendiri. Data enggan dibagi, proses enggan disinkronkan. -
Kurangnya Standar Operasional
SOP antarinstansi kerap berbeda. Apa yang dianggap urgensi oleh satu pihak bisa jadi tidak relevan bagi pihak lain. -
Ketergantungan pada Komando Atas
Banyak koordinasi hanya berjalan jika “perintah dari atas” sudah keluar. Inisiatif bawah kerap tak dianggap. -
Teknologi Belum Terintegrasi
Sistem informasi dan basis data masing-masing institusi belum terhubung, apalagi real-time.
Ambil contoh kebijakan integrasi layanan pendidikan dan kesehatan di daerah. Ketika Dinas Pendidikan ingin mendistribusikan vitamin untuk siswa, sering kali terjadi tumpang tindih data karena data siswa tak sinkron dengan Dinas Kesehatan. Padahal, keduanya bekerja untuk anak yang sama.
Inilah wajah nyata koordinasi yang “gagal rapi”.
Strategi Mengatasi Koordinasi yang Timpang
Beruntungnya, bukan berarti kita tidak punya harapan.
Selama beberapa tahun terakhir, terutama pasca pandemi, ada pergeseran besar dalam cara pemerintah memandang koordinasi. Dari yang dulunya kaku, kini mulai lentur. Dari yang terpusat, mulai melibatkan akar rumput.
Berikut beberapa strategi nyata yang mulai dijalankan:
1. Pembentukan Gugus Tugas Lintas Instansi
Bukan hal baru, tapi kini mulai diimplementasikan lebih dinamis. Gugus tugas ini biasanya berisi perwakilan dari berbagai dinas/instansi yang terlibat dalam satu isu strategis, misalnya stunting, perubahan iklim, atau digitalisasi layanan publik.
2. Digitalisasi Data dan Integrasi Sistem
Program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang digaungkan oleh Kementerian PANRB menjadi tonggak utama. Platform seperti Satu Data Indonesia mendorong seluruh instansi saling berbagi informasi melalui satu ekosistem digital.
3. Pelatihan Koordinatif untuk ASN
Beberapa pemerintah daerah mulai menyisipkan pelatihan soft skill dalam diklat ASN, terutama tentang negosiasi, fasilitasi diskusi lintas sektor, hingga kepemimpinan kolaboratif.
4. Membangun Budaya Sinergi sejak Perencanaan
Pendekatan musrenbang yang kolaboratif dengan melibatkan semua sektor sejak awal perencanaan juga mulai diberlakukan di banyak daerah.
Contohnya bisa dilihat di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan aplikasi e-Musrenbang untuk menjaring aspirasi sekaligus menyinergikan program antar-OPD sejak tahap ide. Ini menghindari duplikasi anggaran sekaligus memperkuat koordinasi di hulu, bukan hanya saat eksekusi.
Anekdot Fiktif – Ketika Koordinasi Berhasil Menyelamatkan Daerah
Di suatu kota kecil bernama Sumber Harapan, musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Debit air sungai menurun drastis. Warga mulai panik. Dinas PU belum bersiap, Dinas Sosial belum punya data, sementara BPBD masih menunggu “surat resmi”.
Namun, seorang sekretaris daerah bernama Bu Yuliani, yang baru 3 bulan menjabat, mengumpulkan seluruh OPD terkait. Ia tak menunggu rapat formal. Ia buat grup WhatsApp dengan kepala OPD, ia pinjam aula sekolah untuk diskusi darurat dan menyusun aksi koordinatif cepat.
Tanpa birokrasi panjang, Dinas PU mengalihkan irigasi darurat. Dinas Kesehatan kirim tenaga medis ke desa rawan air. Dinas Sosial langsung bergerak dengan bantuan logistik. Semua berjalan dalam waktu 5 hari.
Bukan karena anggaran besar. Tapi karena koordinasi yang hidup.
Cerita fiktif ini menggambarkan hal sederhana: ketika ego disingkirkan dan sistem mendukung, koordinasi bisa menjadi kekuatan yang menyelamatkan.
Masa Depan Koordinasi Administrasi Publik di Indonesia
Koordinasi administrasi publik tak lagi bisa hanya mengandalkan struktur vertikal. Ia menuntut pendekatan jaringan, bukan hirarki semata.
Inilah wajah masa depan koordinasi publik:
-
Adaptive Governance
Sistem pemerintahan yang lincah dan belajar dari tiap kebijakan yang dijalankan. -
ASN Kolaboratif
Aparatur yang tak hanya jago teknis, tapi juga mampu menjadi “jembatan” lintas kepentingan. -
Keterbukaan dan Transparansi
Koordinasi yang dibangun atas dasar kepercayaan, dan itu hanya bisa tercipta dengan sistem yang terbuka. -
Penggunaan AI dan Big Data
Integrasi kecerdasan buatan untuk memetakan permasalahan dan solusi lintas sektor secara otomatis.
Namun tentu, teknologi hanyalah alat. Inti dari koordinasi tetap berada di manusia: niat baik, komunikasi terbuka, dan kemauan untuk bergerak bersama.
Jika kita ingin pelayanan publik yang lebih baik, bukan hanya perlu program yang bagus—tapi juga koordinasi yang sungguh-sungguh dijalankan.
Dan itu, dimulai dari para administrator yang mampu menjadi perekat sistem.
Penutup:
Koordinasi administrasi publik bukan sekadar rutinitas birokrasi. Ia adalah detak jantung pelayanan yang tak terlihat, namun sangat terasa. Ketika berjalan baik, publik merasakan kemudahan, keadilan, dan kecepatan. Tapi saat tersendat, yang muncul adalah keluhan, kesenjangan, bahkan krisis.
Maka, menjadi administrator publik bukan pekerjaan sembarangan. Ia adalah profesi strategis, sekaligus panggilan jiwa. Sebab di tangan mereka, koordinasi bukan lagi mimpi—melainkan kenyataan yang terus bekerja dalam senyap.
Baca Juga Konten Dengan Artikel Terkait Tentang: Pengetahuan
Baca Juga Artikel Dari: Kontrol Barang Rusak: Jurus Jitu Biar Stok Gak Bikin Pusing!